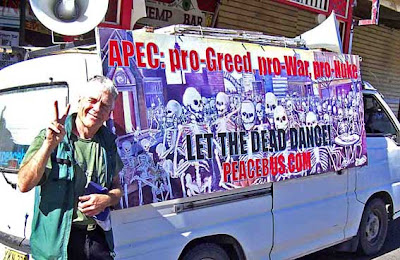Satu Tujuan
Oleh:
(Sejarawan dan Filsuf Swasta,
Alumus Fakultas Filsafat UGM)
Hakikat Manusia
Berbicara tentang kemandirian berarti membicarakan tentang kebebasan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, terlebih dahulu dibutuhkan uraian tentang hakikat manusia. Diharapkan dari penjelasan tersebut akan diketahui sebab-sebab yang menyebabkan manusia bisa memiliki dan sekaligus bisa kehilangan kebebasannya.
Manusia Antara Apa….
Manusia bukan hanya “apa”. Apa maksud kalimat tersebut? Dalam bahasa Indonesia kata “apa” digunakan untuk bertanya tentang benda. Misalnya: “Kursi itu terbuat dari apa?” atau “Meja itu terbuat dari apa?” atau “Itu padi jenis apa?” Dll. Sehingga kata “apa” tidak akan cocok jika digunakan untuk bertanya tentang manusia. Misalnya: “Apa Iwan itu?” Pertanyaan tersebut menurut kaidah kebahasaan jelas tidak tepat.
Kalau begitu, apakah manusia bukan benda material?
Badan manusia—dari ujung rambut sampai ujung kaki—jelas benda material. Sebagai barang material ia harus mengikuti hukum-hukum barang material, yang artinya badan manusia sebagaimana benda-benda yang lain juga mempunyai keterbatasan. Sebagai contonya, organ-organ manusia bisa rusak sebagaimana benda.
…Dan Siapa
Akan tetapi, manusia bukan hanya “apa” melainkan juga “siapa.” Kata “siapa” ini hanya bisa dilekatkan pada manusia dan tidak bisa dilekatkan pada makhluk yang lain. Misalnya: “Siapa kambing itu?” Pertanyaan tersebut bila jelas tidak tepat dalam kaidah kebahasaan. Akan tetapi, pertanyaan ini akan tepat: “Siapa Iwan?” Karena apa? Karena kata “siapa” tersebut dilekatkan pada manusia yang bernama Iwan.
Dari kata “siapa” tersebut secara sadar maupun tidak sadar manusia telah membedakan diri dengan makhluk yang lain. Perbedaan tersebut menyangkut akal budi yang dimilikinya. Hewan mempunyai badan sebagaimana manusia, tapi mereka tidak mempunyai akal sehingga tidak layak disebut “siapa”. Meja, kursi dan lain-lain merupakan benda-benda material seperti halnya tubuh manusia, tapi mereka tidak mempunyai akal sehingga tak layak disebut “siapa”. Hanya manusia-lah yang layak disebut “siapa”.
Manusia Sebagai Siapa
Sebagai “siapa” manusia mempunyai kebebasan yang tak terbatas. Dengan akal budi yang dimilikinya ia bisa menentukan pilihan sesuai dengan yang diinginkannya. Bisa dikatakan manusia mempunyai kebebasan yang tak terbatas.
Dalam ranah filsafat kebebasan manusia memang menjadi pokok perdebatan yang terjadi hingga kini. Dalam filsafat Islam misalnya, terdapat silang pandangan antara kaum Mu’tazilah dan Jabariah mengenai kebebasan manusia. Kaum Mu’tazilah berpendapat bahwa kebebasan manusia tak terbatas. Dengan akal yang dimilikinya ia bisa menentukan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, dengan kebebasan yang dimilikinya manusia harus mempertanggungjawabkan kebebasannya tersebut. Sedangkan kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya, bahwa kebebasan manusia adalah terbatas karena harus tunduk pada kemauan Tuhan. Dalam pandangan mereka manusia tak ubahnya seperti robot, yang bisa bergerak kalau digerakkan atau dengan kata lain apa yang dijalani manusia di bumi ini sudah ditentukan oleh Tuhan.
Perdebatan tentang kebebasan juga terdapat dalam filsafat Barat. Filsuf eksitensialisme seperti Sartre menganggap kebebasan manusia tidak terbatas. Manusia merupakan subjek bukan objek. Pandangan mereka ini kemudian berimbas pada penegasian terhadap Tuhan, karena sebagai subjek manusia tak membutuhkan kehandiran Tuhan. Sedangkan para filsuf idealis seperti Plato menganggap manusia hanya objek yang tunduk pada kemanuan sang Subjek (Tuhan).
Kenyataan Tentang Kebebasan
Kebebasan manusia memang tak terbatas, tetapi sering kali manusia tidak bebas. Sebagai contoh adalah kehidupan para budak. Sebagai manusia sebetulnya ia mempunyai kebebasan tetapi dalam kenyataannya ia tidak bebas karena hidupnya ditentukan pemilik budak. Begitu juga sebuah bangsa yang sebetulnya mempunyai kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri, tetapi bangsa yang terjajah tidak akan mempunyai kebebasan seperti itu.
Itulah kenyataannya, seringkali kebebasan itu terpasung, baik oleh sebab dari dalam maupun dari luar. Keterpasungan ini menyebabkan manusia tidak mampu untuk mandiri. Keterpasungan itu pula yang menyebabkan sebuah bangsa kehilangan kemerdekaannya.
Lalu apa yang bisa dilakukan?
Tiga Jalan, Satu Tujuan
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan manusia mempunyai kebebasan tetapi seringkali kebebasannya terampas. Adanya kenyataan ini mengharuskan manusia harus berjuang agar ia bisa memperoleh kebebasannya sendiri sehingga bisa menentukan segala keinginannya. Begitu pula dengan sebuah negara.
Lantas apa yang bisa dilakukan manusia untuk memperoleh kebebasannya?
Ada tiga jalan yang bisa ditempuh. Dalam menguarikan tiga jalan tersebut penulis akan menggunakan pemaparan yang digunakan oleh Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya ada tiga macam revolusi agar manusia bisa bebas. Pertama, revolusi sebagai perjuangan fisik. Tokoh rekaan dalam karya Pramoedya, khususnya dalam masa-masa revolusi kemerdekaan seperti dalam Perburuan, Di Tepi Kali Bekasi, Dendam, Keluarga Gerilya, Mereka Yang Dilumpuhkan, terlibat dalam sebuah perjuangan yang berbentuk revolusi fisik rakyat Indonesia melawan kolonialisme. Lewat tokoh-tokohnya tersebut Pram ingin mengatakan bahwa kemerdekaan bukanlah suatu barang gratisan yang bisa diperoleh begitu saja, melainkan harus diperjuangkan bahkan sering meminta pengorbanan yang paling besar yang dimiliki oleh manusia.
Revolusi kedua, yaitu revolusi sebagai perjuangan batin. Revolusi dalam makna ini, menurut Pramoedya, adalah sebuah revolusi yang harus bisa mengubah jiwa manusia dari jiwa yang terjajah menjadi jiwa yang merdeka. Revolusi jiwa ini meliputi perjuangan manusia untuk memperoleh keadilan, bebas dari ketakutan, dan memiliki kesamaan hak, sehingga bisa lahir menjadi manusia yang benar-benar merdeka jiwanya.
Adapun revolusi ketiga yaitu revolusi sosial. Dalam pemikiran Pramoedya, keadaan masyarakat perlu diubah melalui sebuah revolusi sosial. Yaitu, mengubah tatanan masyarakat yang menindas menjadi masyarakat yang membebaskan. Ini berarti, revolusi pembebasan nasional saja tidak cukup. Menurutnya, revolusi pembebasan nasional belum bisa menghasilkan sebuah perubahan yang bersifat fundamental, yang kemudian untuk selanjutnya dapat mengubah Indonesia menjadi rumah kemanusiaan yang diharapkan—hanya bersifat reforisme belaka. Dalam tulisan yang berjudul Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, Pram mengatakan dibutuhkan sebuah revolusi proletariat untuk menyempurnakan revolusi pembebasan nasional. Tujuan revolusi ini adalah merebut alat produksi dari tangan borjuasi sehingga bisa mengubah masyarakat kapitalis yang menghisap menjadi masyarakat sosialis yang membebaskan.
Bagi Pram, ketika revolusi berjalan secara dialektik—dan apabila ketiga revolusi ini berhasil—maka akan terciptalah rumah kemanusian yang ideal, yaitu sebagai rumah yang bisa menaungi manusia tanpa adanya penindasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yang diatapi oleh kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, yang berdiri di atas dunia baru: dunia yang dibangun di atas landasan keadilan yang merata.
Dengan tiga jalan di atas tersebut maka manusia/bangsa akan mencapai satu tujuan: kemerdekaan.
Kekuatan Pengubah; Memetakan Musuh
Sebelum berbicara tentang kekuatan pengubah maka terlebih dahulu diperlukan mengurai tentang kekuatan-kekuatan yang merantai kemandirian suatu bangsa, yang menurut pandangan penulis dapat dipetakan menjadi dua, yaitu sebab dari dalam dan dari luar.
Sebab dari dalam merupakan kekuatan-kekuatan di dalam bangsa itu sendiri, yang karena adanya mereka kemandirian tersebut menjadi hilang. Dalam sebuah bangsa mereka bisa direpresentasikan sebagai kelas yang berkuasa—bila mengikuti trias politika mereka tercermin dalam kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Mereka ini sebetulnya merupakan kelas yang minoritas, akan tetapi karena menguasai alat-alat produksi maka mereka menjadi dominan dalam menentukan warna pelanginya sebuah bangsa. Dalam terminologi Marxist mereka ini dikenal dengan sebutan kelas borjuasi.
Dalam sejarahnya, kelas borjuasi ini bisa dikatakan revolusioner—dalam artian mereka mampu mengubah corak produksi dan merombak tatatan masyarakat. Mereka inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan kelas feodal dalam masa revolusi borjuis. Kisah-kisah revolusioner mereka bisa dibaca dari buku-buku sejarah yang mengisahkan tentang revolusi Prancis, atau buku-buku sastra, misalnya karya Victor Hugo, “Si Bongkok dari Notherdam”. Dari bumi Prancis tersebut mereka menjalarkan revolusi ke berbagai tempat. Selanjuntnya, setelah mereka menjadi kelas yang berkuasa élan revolusi mereka menjadi hilang, dan mereka pun berubah menjadi kelas yang anti revolusi.
Berbicara tentang borjuasi dalam konteks Indonesia, mereka tiak dapat dipersamakan dengan borjuasi yang tumbuh dan berkembang di negara-negara Barat. Borjuasi Indonesia bukanlah kelas yang lahir dengan sendirinya, mereka merupakan kelas yang tumbuh dari cangkokan. Mereka pada awalnya merupakan para feodal-feodal pada masa kolonialisme Belanda, yang karena kemuruhan hati Belanda berubah menjadi borjuasi. Sifatnya yang demikian inilah yang membuat mereka tak pernah menjadi mandiri karena tulang-tulang dalam diri mereka tak pernah beranjak dari tulang rawan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau mereka selalu tergantung pada kekuatan yang lebih kuat agar bisa berdiri tegak, artinya mereka tak akan mampu bisa mandiri. Sehingga, berharap agar mereka mengantarkan bangsa ini menuju kemandirian sama halnya menunggu Godot.
Sekerang jelaslah siapa musuh yang pertama: Borjuasi Indonesia, yang saat ini tercermin dari pemerintahan SBY-JK beserta kroni-kroninya. Mereka inilah kepanjangan tangan dari kapitalisme internasional. Sehingga jelaslah bahwa agar tidak merintangi jalan menuju kemandirian Indonesia, mereka harus digulingkan.
Siapakah musuh selanjutnya?
Musuh yang kedua ini sudah merasuk dalam segala aspek kehidupan manusia. Wajah mereka ada dalam sistem ekonomi, politik, budaya, agama, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Sebagaimana halnya dengan Dasamuka dalam kisah Ramayana, mereka itu satu tetapi berwajah banyak. Mereka inilah yang dikenal dalam terminologi Marxist sebagai kapitalisme, yang merupakan anak kandung dari borjuasi.
Sebagaimana halnya borjuasi, sebagai sistem ekonomi mereka pada awalnya revolusioner, di mana berhasil merombak tatanan ekonomi feodal menjadi tatanan ekonomi kapitalis. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya sistem ekonomi ini akahirnya menjadi sistem yang menindas akibat ciri khasnya yang eksploitatif—baik terhadap sumber daya alam maupun terhadap kelas proletar.
Tentang sistem kapitalisme ini JJ Rousseau berpandangan bahwa sistem ini telah mencabut keadaan bahagia manusia di Taman Eden, sehingga manusia mengalami keterasingan (alienasi). Sedangkan Karl Marx mempunyai penadapat serupa tetapi lebih menekankan pada kepemilikan hal milik sebagai penyebab keterasaingan, dan perjuangan kelas sebagai jalan untuk melepaskan diri dari alienasi (istilah ini bisa dicaca sebagai ketidakmandirian). Sedangkan Gothe memberikan jalan keluar agar manusia bisa terbebas dari alienasi tersebut melalui tiga penghargaan, yaitu penghargaan kepada yang ada di bawah manusia (mineral, flora dan fauna); penghargaan terhadap Dzat yang berada di atas manusia (Tuhan dan alam akhirat); dan penghargaan kepada sesama manusia.
Di antara pendapat-pendapat tersebut di atas memang Karl Marx yang paling gigih dalam memberikan jalan keluar—baik melalui teori maupun pratek. Konsep Marx agar manusia menjadi bebas tercermin dalam karya-karyanya—baik dalam Das Kapital maupun karya-karya yang lain. Dalam karya-karya tersebut secara garis besarnya ia memaparkan bahwa manusia hidup dalam ketidakmandirian karena adanya kepemilikan pribadi. Bagi Marx agar manusia bisa kembali mandiri maka harus melakukan perjuangan kelas yang dipimpin oleh kelas proletar, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat komunis. Sedangkan dalam tataran praktek, konsep Marx bisa dilihat dari kerja-kerja politiknya dalam pembangunan kekuatan politik proletar pada abad ke-19. Dalam tataran praktis ini ia mengusulkan terbentuknya sebuah partai proletar.
Nah, sekarang musuh yang kedua sudah kita ketahui: kapitalis internasional, yang sekarang ini mereka mewujud dalam istilah pada aktivis dengan sebutan neoliberalisme.
Satu Kata Yang Hilang
Bicara tentang kekuatan pengubah tentu saja berbicara tentang kekuatan-kekuatan politik yang sekarang ada di Indonesia. Bila dicermati tentang kekuatan-kekuatan politik yang tumbuh berkembang saat ini—dalam hal ini yang dimaksud tentang kekuatan-kekuatan politik tentu saja kekuatan yang berlawan, atau awam sering menyebutnya sebagai kekuatan opoisi—ada satu kata yang hilang dari mereka. Yiatu, “Gulingkan”. “Gulingkan” yang dimaksudkan di sini adalah “gulingkan” rezim borjuasi (SBY-JK).
Sebelum era revolusi demokratik yang terinterupsi (baca:revolusi Mei ’98) kata “gulingkan” ini menjadi kata yang sangat ditakuti baik oleh berbagai kekuatan yang berlawan maupun oleh rezim ketika itu (Soerharta, Golkar dan tentara). Sepengetahuan penulis, kata “gulingkan” pertama kali diperkenalkan oleh PRD (Partai Rakyat Demokratis), yang kemudian kata tersebut menjelma menjadi program ideologi, politik maupun organisasi mereka. Sampai pada masa pemerintahan Megawati Sukarno Putri, kata “gulingkan” ini masih ada dalam program PRD. Akan tetapi, sejak SBY-JK mulai berkuasa, kata “gulingkan” tersebut melenyap dari PRD maupun Papernas (partai yang kelihatannya dipersiapkan untuk pemilu 2009, yang merupakan gabungan dari PRD dan kekuatan-kekuatan politik yang lain)—baik menghilang dalam tataran program maupun pratek di lapangan (mungkin saja dicantumkan dalam program untuk menunjukkan bahwa mereka masih konsisten, tapi hanya untuk kalangan internal, tanpa pernah dikampayekan (propagandakan) secara luas.
Hilangnya kata “gulingkan” dari PRD rupanya juga diikuti oleh kekuatan-kekuatan politik yang berlawan lainnya. Kekuatan mahasiswa yang walaupun seringkali naif tapi cukup “berani” dalam melontarkan program politik dan metode perjuangan, saat ini sudah jarang (mungkin tidak pernah) mengangkat meneriakkan kata “gulingkan” ini. Mereka lebih sibuk mengurusi isu-isu “dosmetik” yang tidak memberikan perspektif perjuangan jangka panjang.
Kondisi yang sama juga terjadi pada organisasi-organisasi Kaum Miskin Perkotaan (KMK), yang gagal menghubungkan misalnya, antara program penggusuran dengan pengulingan rezim SBY-JK. Akibatnya, mereka hanya memperoleh “kemenangan-kemenangan kecil” yang seringkali mengilusi. Padahal, bila organisasi-organisasi KMK ini mampu menghubungkan program-program mereka dengan penggulingan SBY-JK, energi revolusi mereka sangat besar, karena di samping kaum proletar, KMK-lah yang paling banyak mendapat dampak langsung dari kebijakan SBY-JK yang menghamba pada kekuatan kapitalisme internasional. Menurut hemat penulis kegagalan organisasi-organisisasi KMK tersebut terjadi karena sebuah kekuatan yang sebetulnya bisa menjadi “picu ledak” bagi proses revolusi justru dipimpin oleh orang-orang yang moderet, yang tidak mengetahui karakter sejati dari kelas yang dipimpinnya.
Gerakan buruh pun setali tiga uang. Secara potensi massa yang bisa dikerahkan memang mengali peningkatan, tapi secara program perjuangan mereka mengalami kemunduran. Para pemimpin gerakan buruh yang sebagian besar kaum buruh berdasi ini mengarahkan gerakan buruh ke arah yang moderat. Akibatnya, seradikal apapun metode perjuangannya, tak banyak membawa dampak yang cukup berarti.
Dalam pandangan penulis, hilangnya kata “gulingkan” ini membuat rezim SBY-JK pun bisa melenggang kangkung dengan leluasa. Bisa dikatakan inilah keberhasilan dari SBY-JK dalam memoderasi program penggulingan borjuasi dari kekuatan-kekuatan politik yang berlawan yang ada saat ini.
Penulis sendiri belum bisa melihat akar penyebab dari hilangnya kata “gulingkan” tersebut. Akan tetapi, bila melihat dari perkembangan politik kekinian dapat dilihat bahwa hilangnya kata “gulingkan” lebih banyak disebabkan oleh pramagtisme dari kekuatan-kekuatan politik yang berlawan. Setelah gagal menuntaskan revolusi demokratik yang terinterupsi, kekuatan-kekuatan politik yang berlawan menjadi patah arang—disebabkan oleh kesalahan mereka dalam melihat proses kemajuan maupun kekurangan dalam perjuangan—sehingga mereka lebih memilih cara-cara yang pragmatis, yaitu parlementerisme.
Bagi penulis, jalan parlementer sama dengan kisah Musa dalam Bible maupun al Qur’an. Ketika Musa terusir dari Mesir konon kabarnya Tuhan menjanjikan pada Musa dan kaumnya “tanah yang dijanjikan”, yaitu Yerusalem. Adanya janji tersebut membuat pengikut Musa rela menempuh marabahaya dan berjalan ratusan kilometer untuk melakukan eksodus dari Mesir menuju “tanah yang dijanjikan”.
Jalan parlementer juga seperti “tanah yang dijanjadikan”. Kondisi kekuatan-kekuatan politik berlawan yang patah arang (demoralisasi) membuat mereka membutuhkan harapan baru berupa jalan parlementer—yang dengan jalan ini mereka berharap dapat mencapai segala sesuatunya. Di satu sisi jalan keluar ini memenang mampu menghasilkan suatu harapan baru, tetapi harapan ini justru menjerumuskan mereka keliang kubur karena hanya merupakan ilusi—sebagaimana manusia yang berbuat kebaikan mengilusikan mendapat surga yang di dalamnya terdapat bidari-bidari yang terus-menerus perawan, maka manusia seperti ini menurut seorang sufi kenamaan Baghdad (Irak), Rabiah Adawiyah, hanya akan mendapatkan kesia-siaan, maka ia bermaksud membakar surga agar manusia tak tertipu lagi, Rabiah juga mengajukan satu pertanyaan yang menarik, “Apakah kalau tak ada iming-iming surga engkau masih mau menyembah Tuhan, wahai saudaraku? Dalam konteks kekinian pertanyaan tersebut bisa diubah, “Apakah kalau tidak ada iming-iming parlemen engkau masih mau berjuang, wahai kawanku?”. Inilah dampak dari jalan parlementer: munculnya ilusi di antara kekuatan-kekuatan politik yang berlawan. Akibat tersebut masih bisa ditambah dengan munculnya makelar politik dan koruptor serta dampak-damak negatif lainnya.
Sedangkan bagi perkembangan politik yang luas jalan parlementer tidak mengajarkan apa-apa bagi massa rakyat. Selama ini massa rakyat sudah teracuni kesadarannya (terhegemoni) bahwa perubahan hanya bisa ditempuh dengan jalan parlementer—sebagai jalan yang paling demokratis bagi ukuran borjuasi—maka akan semakin teracuni dengan pilihan politik kekuatan-kekuatan yang berlawan, mereka pun tidak lagi bisa melihat jalan alternatif—karena guru mereka mengkhianati jalan mereka sendiri.
Bila menilik ke belekang sejarah Indonesia, jalan parlementer ini sudah ditempuh oleh kekuatan politik yang berlawan ketika itu, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Strategi mereka ini memang berhasil memperluas struktur ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dicapai, namun struktur yang mereka hasilkan ini merupakan struktur tulang rawan yang mudah dipatahkan oleh kekuatan kontrarevolusi. Dan, takdir sejarah pun telah mencacat bahwa mereka—PKI dan kekuatan-kekuatan politik yang beralifiasi dengannya—hancur dan tak mampu bangkit lagi. Kalaupun mau mengambil nilai-nilai positif yang bisa didapat dari sejarah PKI tersebut adalah kemampuan mereka dalam memperluas struktur—yang seandainya mereka tidak menempuh cara-cara yang pragmatis, tentu saja struktur mereka akan kuat—selain hal tersebut apa yang dihasilkan PKI hanya sampah dan ampas.
Munurut pandangan penulis, yang dibutuhkan massa rakyat saat ini adalah cara dan jalan yang benar untuk mengapai kebebasan. Fakta-fakta yang terekam selama ini menunjukkan bahwa mereka sebetulnya mempunyai energi yang besar untuk melawan, tetapi mereka tidak mengetahui cara dan jalan yang benar. Untuk itu kekuatan-kekuatan politik yang berlawan perlu mengajarkan cara dan jalan yang benar tersebut, sehingga massa rakyat sadar bahwa bukan cara dan jalan parlementer yang bisa melepaskan mereka dari belenggu ketidakmandirian, tetapi revolusi-lah—revolusi dalam konteks ini adalah ketiga macam revolusi yang telah dipaparkan di atas— yang bisa membebaskan.
Memunculkan Kembali Kekuatan Yang Hilang
Penulis tidak yakin kalau komunitas seperti Jaringan Kaum Muda untuk Kemandirian Nasional—walaupun mungkin di dalamnya berisi orang-orang progresif-revolusioner—akan mampu memimpin proses perjuangan yang telah dipaparkan di atas. Penulis juga tidak yakin kalau LSM maupun organisasi sejenisnya mampu melakukan tugas sejarah ini. Karena apa? Organisi-organisi tersebut tak akan mampu memikul beban sejarah yang harus ditanggung. Menurut pandangan penulis, hanya sebuah organisasi yang rapi, yang dipimpin oleh para profesional, dan bertulangpunggungkan kekuatan revolusionerlah yang akan mampu menanggung beban sejarah tersebut. Kekuatan tersebut hanya bisa mewujud dalam bentuk partai politik yang revolusioner.
Lantas partai politik apa yang bisa memimpinnya?
Sejarah bangsa Indonesia sebenarnya sudah melahirkan sebuah partai politik yang mampu menanggung beban sejarah tersebut, yaitu PRD. Partai ini lahir sebagai kebutuhan sejarah untuk melahirkan sebuah organisasi revolusioner guna memimpin proses perubahan di Indonesia. Sebagai bagian dari proses sejarah, PRD bukan lahir tiba-tiba, akan tetapi melalui proses yang panjang, yang bila dirunut ke belakang merupakan kelanjutan dari kekuatan-kekuatan politik revolusioner yang ada dalam sejarah Indonesia; ia merupakan sintesis dari gerakan revolusioner itu sendiri—yang tidak hanya melahirkan kader-kader yang revolusioner tetapi juga ideologi revolusioner. Bagi yang tidak mengerti sejarah maka PRD akan dianggap sebagai kumpulan anak muda yang kekiri-kirian, sedangkan bagi penguasa ia akan dianggap sebagai mimpi buruk.
Sebagai bagian dari proses sejarah dari kekuatan revolusioner di Indonesia, potensi yang dimiliki PRD cukup besar. Ini yang membuat kekuatan borjuasi (termasuk tentara) berkali-kali mencoba menghancurkannya—mulai dari penangkapan, penculikan sampai pembunuhan. Menghadapi hantaman-hantaman tersebut PRD mampu melaluinya. Ia terus bertumbuh di antara musuh-musuh politik yang terus-menerus mengincar. Akan tetapi, begitu menghadapi ruang demokratik yang dibukanya sendiri, kader-kadernya menjadi gagap. Sebagai kader-kader yang seringkali bergerak di bawah tanah mereka silau melihat hasil perjuangan sendiri. Mereka menjadi tak mampu mengeja yang terjadi, mengurai yang tersirat maupun tersurat. Akibatnya, mereka menjadi larut dan lupa akan jati dirinya sendiri. Maka tak mengherankan kalau kemudian muncul petualang-petualang politik yang menggerogoti PRD dari dalam. Dengan kata lain, ia kalah oleh dirinya sendirinya, bukan oleh lawan-lawan politiknya.
Sebetulnya dengan munculnya kader-kader baru keadaan tersebut bisa diatasi. Akan tetapi sayang, kader-kader baru tersebut hanya mengelus-ngelus masa lalu PRD; PRD dulu revolusioner, PRD dulu memelopori pengulingan Suharta, PRD dulu ini dan itu. Mereka hanya mengelap kejayaan masa lalu tanpa mampu melahirkan kejayaannya sendiri. Tak mengherankan kalau dalam perkembangan terkini, PRD justru menjadi kuda troya bagi petualang-petualang politik yang ada di dalamnya bukan sebagai pelopor dari kekuatan-kekuatan yang berlawan. Situasi ini memang membawa kemunduran dari PRD, tetapi di sisi lain merupakan berkah karena para kader-kadernya akan bisa melihat mana yang loyong dan mana yang emas.
Proses kemunduran tersebut merupakan takdir sejarah PRD yang bukan berarti tidak bisa diubah. Ia bisa keluar dari masa-masa kemundurannya ini, keluar menjadi kekuatan baru yang lebih kuat dari sejarah masa lalunya, dengan syarat ia mampu merevolusi dirinya sendiri, mampu melihat dirinya pada titik yang benar, mampu menghargai apa yang telah dihasilkan, mampu mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Tentu saja seperti kelahirannya, proses ini tidak semudah membalik telapak tangan, ia membutuhkan proses yang panjang. Sebagai partai yang lahir dari “kehendak zaman” ia harus bekerja keras agar maqom (kedudukannya) dalam pentas perjuangan revolusioner Indonesia bisa didapatkan kembali.
Akhirnya, sebagai penutup tulisan ini penulis ingin mengajukan satu pertanyaan: Apakah “kekuatan yang hilang tersebut” bisa muncul kembali? [*]
Lereng Gunung Merapi, 19 September 2007
(Tanggapan atas tulisan ini
bisa ditujukan
pada alamat: ragil_nugroho1@yahoo.com.
Tentu saja tanggapan yang cerdas yang ditunggu)